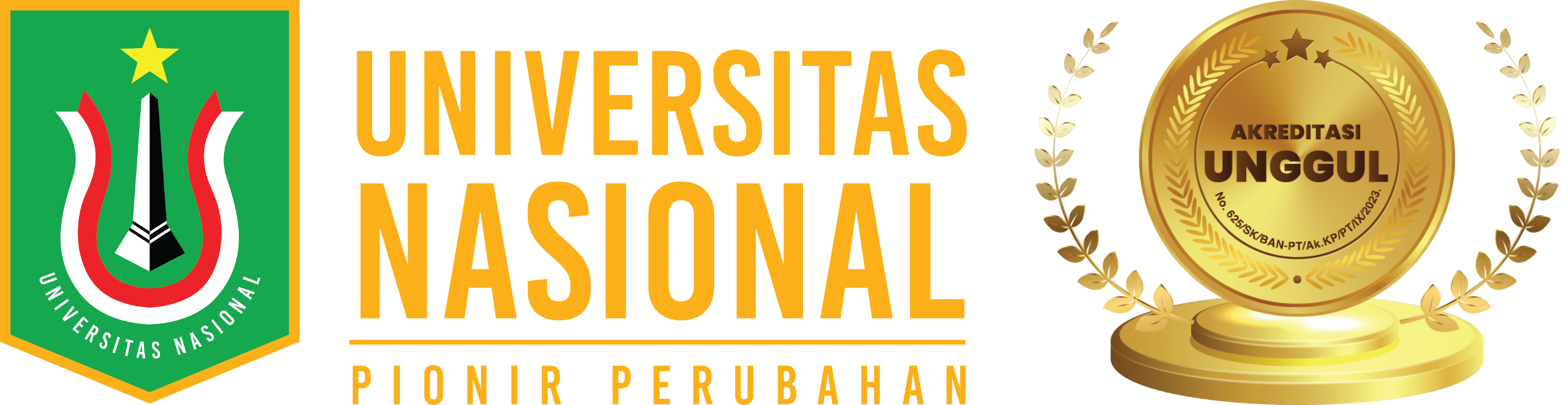Jakarta (UNAS) – Mudik bukan sekadar perjalanan pulang kampung, tetapi juga fenomena sosial yang mencerminkan keterikatan individu dengan akar budayanya. Dalam perspektif sosiologi budaya, mudik dapat dikaitkan dengan konsep habitus dari Pierre Bourdieu, di mana kebiasaan ini menjadi bagian dari struktur sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi mudik juga memperlihatkan konsep solidaritas mekanik yang dikemukakan oleh Emile Durkheim, di mana masyarakat yang memiliki kesamaan nilai dan norma merasa perlu kembali ke komunitas asalnya. Lebih dari sekadar ritual tahunan, mudik juga berfungsi sebagai bentuk reproduksi sosial, memastikan bahwa hubungan kekeluargaan dan nilai-nilai tradisional tetap bertahan di tengah arus modernisasi. Dengan demikian, mudik menjadi mekanisme yang menjaga keseimbangan antara mobilitas sosial dan keterikatan budaya dalam kehidupan masyarakat.
Bagi kaum urban, mudik memiliki makna yang lebih kompleks karena mencerminkan dinamika kehidupan masyarakat perantauan. Fenomena ini dapat dianalisis melalui teori mobilitas sosial yang menjelaskan bagaimana individu berpindah dari satu kelas sosial ke kelas lainnya dalam struktur masyarakat. Sebagai pendatang di kota besar, kaum urban sering kali dihadapkan pada tantangan integrasi budaya, sehingga mudik menjadi cara untuk menegaskan identitas sosial mereka. Dalam teori interaksi simbolik George Herbert Mead, mudik juga dapat dipahami sebagai simbol dari pencapaian ekonomi dan keberhasilan hidup di perantauan. Melalui perjalanan mudik, para perantau tidak hanya kembali ke kampung halaman, tetapi juga membawa serta status sosial baru yang diperoleh dari kehidupan urban mereka.

Dari perspektif fungsionalisme struktural Talcott Parsons, mudik memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial melalui mekanisme rekoneksi emosional dan sosial. Bagi kaum urban yang hidup di lingkungan heterogen dan kompetitif, pulang ke kampung halaman memberikan kesempatan untuk kembali pada nilai-nilai kolektif yang lebih harmonis. Selain itu, mudik juga mencerminkan konsep ritual kolektif dari Clifford Geertz, di mana perjalanan ini tidak hanya menjadi ajang pertemuan keluarga, tetapi juga sebagai bentuk ekspresi budaya yang memperkuat rasa kebersamaan. Dengan demikian, tradisi mudik berfungsi sebagai jembatan antara kehidupan modern yang individualistis dan akar budaya yang berbasis komunal.
Dalam konteks ekonomi dan budaya, mudik juga menjadi fenomena yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Berdasarkan konsep globalisasi budaya, mudik mencerminkan bagaimana perantau membawa serta budaya kota ke desa, menciptakan pertukaran sosial yang dinamis. Banyak daerah yang menggantungkan perekonomiannya pada arus mudik, di mana konsumsi meningkat secara signifikan selama periode ini. Selain itu, teori kapital sosial yang dikembangkan oleh Robert Putnam menjelaskan bahwa mudik memperkuat jaringan sosial yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan pendidikan. Oleh karena itu, mudik bukan hanya tradisi personal, tetapi juga memiliki dampak makro dalam sistem sosial yang lebih luas.


Di Universitas Nasional, Program Studi Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) mengkaji berbagai fenomena sosial, termasuk budaya mudik, dengan pendekatan akademik yang mendalam. Sebagai universitas swasta pertama di Jakarta, UNAS berkomitmen untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai fenomena sosial melalui kajian sosiologi kritis dan terapan. Mahasiswa Sosiologi UNAS didorong untuk melakukan penelitian mengenai dinamika sosial masyarakat urban dan tradisi budaya seperti mudik guna memahami pergeseran pola sosial di era modern. Dengan kurikulum yang berbasis riset dan kajian teoritis, mahasiswa UNAS dapat menganalisis bagaimana perubahan sosial terjadi di tengah globalisasi dan modernisasi. Dengan demikian, lulusan Sosiologi UNAS diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam memahami dan memecahkan berbagai permasalahan sosial yang ada di masyarakat.(*MPR)
Bagikan :